Balasan Surat Kumala
Hakim masih saja tenggelam asyik dalam bacaannya,
sementara waktu terus berganti, bergulir, berlomba, sedetikpun yang terlewatkan
tak akan pernah kembali. Bahkan jika seluruh perbendaharaan harta di muka di
tukargulingkan. Perjuangan melepaskan kecanggungan yang amat berat haruskah
terjawab dengan kelupaan? Padahal tak mudah Kumala menitikkan huruf demi huruf,
menorehkan kata demi kata, hingga terjalin utuh menjadi sepucuk surat.
Tidakkah ia tahu bahwa Kumala, wanita yang telah
hijrah itu, menunggu balasan suratnya. Apakah kejadian malam purnama itu
benar-benar telah membuatnya harus menghujat Kumala berulang kali? Masihkah ia
harus mencapnya dengan cemooh yang bahkan tak diinginkan oleh siapapun? Surat
misterius yang masih saja misterius dalam tas.
Rutinitas hariannya, membuatnya benar-benar larut.
Ia sampai lupa akan surat misterius dalam tas itu. Mambang kuning di ufuk barat
terdesak oleh gelap perlahan demi perlahan mulai hengkang. Azan magrib telah
berkumandang, panggilan yang meneduhkan setiap jiwa untuk kembali kepada Sang
Penguasa Semesta Raya, Hayya alash-Shalah,
Hayya alal-Falah.
Di seberang sana Kumala masih menantikan balasan
surat itu. Sesekali ia kerap menyalahkan dirinya, ragam macam prasangka
membuntuti. Jika saja ia tidak menulis surat itu. “Sampai sebegitu beraninya
saya menulis dan mengirim surat itu!”, “Kok,
belum ada balasannya?”, “Apa belum sampai suratnya?”, seribu satu tanya,
menari-nari mengitari. Apalah daya surat telah dilayangkan, belum juga ada jawaban.
Waktu terus bergulir, Hakim dalam rutinitasnya yang
khilaf akan keberadaan surat dalam tas. Kumala dengan seribu satu tanya, menanti
balasan yang tak kunjung tiba. Sejak jumat hingga ahad, Hakim tidak ada jadwal
kuliah. Saat demikian ini akan banyak menyibukkan diri di organisasi ekstranya,
tas kuliahnya ia titipkan di kamarnya.
Ahad malam ia kembali ke kamar. Menyiapkan beberapa
untuk persiapan kuliah senin besok. Saat itulah ia melihat surat misterius itu.
“Ah, ini surat Kamis lalu!”, segera saja
ia melepas amplop surat itu. “Surat dari siapa ya?”, bisiknya.
Matanya hanyut pada setiap bait dalam surat itu. “Ini
tulisan tangan Kumala”, ia mengenal tulisan tangan itu. Ada senyum tulus
tersimpul di bibirnya. “Alhamdulillah!”, ucapnya. Konsentrasinya terpusat pada
bait surat terakhir. Beberapa kali ia coba membaca kembali dan ternyata tulisan
tangan tetap tidak berubah. Ia mulai mencubit kulitnya, kemudian mencubit
kembali, “Ah, sakit! Ini bukan mimpi”,
ucapnya.
Setelahnya lama benar ia termenung. Mimik bahagia
yang tertahan dan keraguan yang menghantui. Pikirannya benar-benar kalut malam
itu. Ia memikirkan orang tuanya, kedua adiknya, kuliahnya, cita-citanya. Akhirnya
ia putuskan mengambil telepon selulernya, mengirimkan pesan kepada Kumala.
“Assalamu’alaikum..
Suratmu telah
kubaca. Afwan, saya masih punya cita-cita yang harus saya wujudkan..
Syukran..
Wassalam..”Demikianlah balasan surat kumala. Ungkapan itulah yang paling baik menurut Hakim saat itu. Di tengah kebimbangan yang amat, tuntutan untuk menyelesaikan kuliah. "Anak pertama selalu menjadi harapan bagi orang tua, ia diharapkan mengangkat nama keluarga, diharapkan menjadi jembatan kesuksesan bagi adik-adiknya", kata-kata ini yang paling ia takuti dan ia coba perjuangkan.
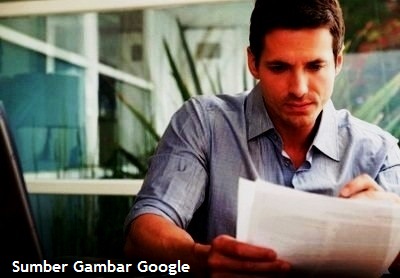



Komentar
Posting Komentar